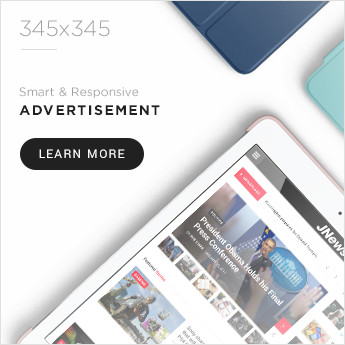Jakarta, IDN Times – Kabar kurang menggembirakan datang dari dunia ketenagakerjaan Indonesia. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan temuan yang cukup mencolok, yakni peningkatan signifikan proporsi pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Menurut peneliti Celios, Bara, peningkatan ini terbilang drastis, melonjak dari 63 persen pada tahun 2021 menjadi 84 persen pada tahun 2024. “Kami menemukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMR meningkat tajam dari 63 persen pada 2021 menjadi 84 persen pada 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (31/5/2025).
Celios juga menyoroti beberapa permasalahan lain terkait dunia kerja, seperti jam kerja yang berlebihan dan data korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai belum komprehensif.
Bara berpendapat bahwa data pengangguran yang dirilis pemerintah belum sepenuhnya mencakup pekerja di sektor informal. Ia juga menyoroti minimnya data yang relevan untuk perumusan kebijakan yang disampaikan kepada publik. Sebagai contoh, industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mencatatkan persentase tertinggi pekerja dengan jam kerja berlebihan, rata-rata mencapai 48 jam per minggu. Bahkan, pekerja ojek online memiliki jam kerja yang lebih panjang lagi, yakni rata-rata 54,5 jam per minggu, jauh di atas rata-rata pekerja lainnya yang hanya 41,5 jam per minggu.
“Kami mendorong adanya data tenaga kerja yang lebih akurat mengenai pekerja di gig economy, sejalan dengan maraknya perpindahan dari korban PHK ke pekerja informal,” imbuh Bara. Hal ini penting untuk memahami dinamika pasar kerja yang berubah dengan cepat.
Temuan Celios ini menambah daftar permasalahan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius. Sebelumnya, Celios juga sempat menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang dinilai stagnan di level 5,03 persen.
Selain masalah upah dan jam kerja, Celios juga menyoroti metodologi pengukuran kemiskinan yang dinilai sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Celios menilai bahwa metodologi pengukuran kemiskinan nasional yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama hampir lima dekade sudah tidak lagi relevan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara data BPS yang mencatat 8,5 persen penduduk sebagai miskin dan data Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen penduduk masuk kategori miskin menurut standar 6,85 dolar AS PPP per hari.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa pendekatan lama yang berbasis kecukupan kalori dan indikator pengeluaran tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan masa kini. Faktor-faktor seperti beban utang, ketimpangan akses layanan publik, dan tekanan finansial rumah tangga kelas menengah tidak terakomodasi dalam pengukuran tersebut.
“Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan,” tambahnya. Media juga menjelaskan bahwa penggunaan kelompok rentan sebagai referensi perhitungan garis kemiskinan membuat garis tersebut tidak naik signifikan, meskipun daya beli masyarakat terus memburuk. Akibatnya, alokasi anggaran dan skema bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran, sementara persentase anggaran perlindungan sosial terhadap PDB Indonesia tetap rendah.
Sebelumnya, aturan terbaru Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diklaim mampu menyelamatkan 1,7 juta pekerja dari potensi PHK. Namun, Celios berpendapat bahwa upaya lain juga diperlukan, terutama dalam hal perbaikan data dan metodologi pengukuran.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Celios mengusulkan perubahan garis kemiskinan dan strategi baru yang lebih komprehensif.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan bukanlah hal yang tabu. Ia mencontohkan Malaysia yang pada tahun 2019 memperbarui garis kemiskinannya untuk memperbesar porsi bantuan sosial. Menurut Bhima, berbeda dengan Malaysia, pemerintah Indonesia tampak khawatir kenaikan angka kemiskinan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apalagi di tengah rasio pajak yang rendah dan meningkatnya utang jatuh tempo.
“Tapi di sisi lain langkah BPS yang belum juga merevisi garis kemiskinan justru terkesan membatasi hak orang yang benar-benar miskin dari akses bantuan pemerintah,” kata Bhima. Ia juga menyoroti masalah akurasi data yang berdampak pada efektivitas stimulus pemerintah, mencontohkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Juni-Juli 2025 yang lalu yang dinilai menciptakan ketimpangan. “Sepertinya saat ini mengulang kesalahan yang sama dimana banyak pekerja informal, pekerja kontrak, ojol, dan pekerja outsourcing tidak mendapat BSU karena persoalan pendataan,” ungkap Bhima.
Celios mengusulkan redefinisi pengukuran kemiskinan dengan pendekatan berbasis disposable income, yang mempertimbangkan pendapatan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi, serta faktor geografis dan kebutuhan nonmakanan. Sebagai referensi, Uni Eropa telah menerapkan pendekatan hidup yang layak yang mencakup indikator literasi, kesehatan, pengangguran, hingga kebahagiaan.
Celios juga mendorong pemahaman bahwa data kemiskinan seharusnya berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan, bukan alat politik. Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi fiskal, pemerintah dapat menilai efektivitas program redistribusi seperti Makan Bergizi Gratis, PKH, atau subsidi pupuk. Untuk mendorong perubahan, Celios merekomendasikan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar koordinasi lintas lembaga dalam menyusun indikator baru, memperkuat integrasi data, dan menyelaraskan program pengentasan kemiskinan secara nasional.
Ringkasan
Lembaga riset Celios menemukan peningkatan drastis pada proporsi pekerja dengan upah di bawah UMR, melonjak dari 63% di 2021 menjadi 84% di 2024. Selain masalah upah, Celios juga menyoroti jam kerja berlebihan, data PHK yang belum komprehensif, dan metodologi pengukuran kemiskinan yang dinilai usang. Data pengangguran pemerintah dinilai belum mencakup pekerja sektor informal, dan minimnya data relevan menghambat perumusan kebijakan yang tepat.
Celios mengusulkan perubahan garis kemiskinan dan strategi baru yang lebih komprehensif, termasuk redefinisi pengukuran kemiskinan dengan pendekatan berbasis disposable income. Mereka mendorong pemahaman bahwa data kemiskinan seharusnya menjadi alat evaluasi kebijakan, bukan alat politik. Celios merekomendasikan penerbitan Perpres untuk koordinasi lintas lembaga dalam menyusun indikator baru dan menyelaraskan program pengentasan kemiskinan.