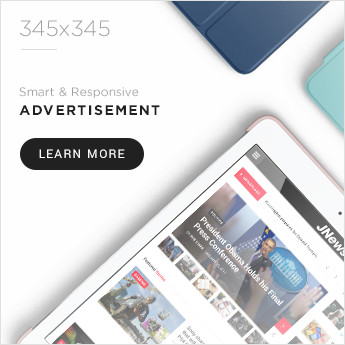Polemik mengenai penetapan status bencana nasional untuk banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatra masih terus bergulir. Perdebatan ini memicu pertanyaan krusial: seberapa besar sebenarnya dampak status tersebut di lapangan, jika dibandingkan dengan peristiwa dahsyat seperti Tsunami Aceh 2004 dan Likuifaksi Palu?
Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah dilakukan dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian, yakni 26 Oktober. Menurut Seskab Teddy, respons yang dilakukan adalah “mobilisasi nasional” dengan mengerahkan lebih dari 50 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan relawan ke wilayah terdampak. Ia juga membantah anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, dukungan anggaran pusat tidak dapat tersalurkan. “Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat, disampaikan Rp60 triliun, sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya,” ujar Seskab.
Namun, di sisi lain, seorang relawan veteran, Ira Hadiati, yang memiliki pengalaman dalam penanganan Tsunami Aceh 2004 dan kini terlibat di banjir Sumatra, berpandangan bahwa tanpa status bencana nasional, penanganan di lapangan “masih menghadapi kendala koordinasi dan belum gerak cepat”. Ira menjelaskan perbedaan mendasar antara “perintah” dan “komando”. Status bencana nasional akan menempatkan komando langsung pada Presiden, memastikan semua pihak bergerak serempak. Dalam situasi saat ini, koordinasi antar kementerian seringkali memerlukan diskusi berjenjang, yang menghambat kecepatan eksekusi.
Dampak kendala koordinasi ini sangat terasa pada perbaikan fasilitas krusial seperti jalan dan jembatan, yang vital untuk membuka akses ke area terisolir. Ira mencontohkan Jembatan Awe Geutah yang membutuhkan waktu lama untuk bisa dilalui sebagai alternatif penghubung Bireuen-Lhokseumawe atau Banda Aceh-Medan, sementara Jembatan Kuta Blang masih terputus. Hal ini berbeda jauh dengan pengalaman Tsunami Aceh 2004, di mana status bencana nasional memungkinkan pembangunan jalur krusial segera diselesaikan karena adanya satu komando dan penanggung jawab tunggal, didukung penuh oleh berbagai pihak, termasuk bantuan internasional. Kondisi saat ini juga jauh lebih menantang karena lokasi terdampak di Aceh mencapai 18 kabupaten, lebih banyak dari Tsunami 2004.
Senada dengan Ira, Videl Jemali, seorang warga yang menjadi korban Gempa dan Likuifaksi Palu pada 2018—bencana yang juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional—menyoroti peran penting bantuan internasional dalam mempercepat penanganan darurat. Videl mengenang bahwa di Palu, distribusi bantuan dari pusat sempat tersentralisasi di Korem dan tidak merata, seringkali habis sebelum sampai ke semua yang membutuhkan. Barulah setelah tiga minggu pascabencana, ketika bantuan dari luar (internasional) mulai masuk dan relawan mendistribusikan langsung ke tenda-tenda pengungsian, bantuan mulai terasa lebih merata.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menekankan pentingnya penanganan pascabencana yang masif dan kolaboratif. Ia mengkritik pandangan pemerintah yang merasa sanggup menangani sendiri, yang menurutnya dapat melemahkan peran komponen non-pemerintah dan bantuan internasional. Menurut Avianto, bantuan internasional adalah keniscayaan dan bentuk solidaritas kemanusiaan saat bencana besar melanda, bukan menciderai harga diri bangsa, melainkan memperkuat hubungan dan persatuan global.
Seskab Teddy Indra Wijaya, dalam jumpa pers lainnya, menegaskan pentingnya kekompakan dalam penanganan bencana. Ia memastikan bahwa TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB daerah telah bergerak sejak hari pertama. Dukungan langsung juga diberikan kepada kepala daerah terdampak, termasuk uang tunai untuk kebutuhan mendesak. Lebih dari 100 kapal, pesawat, helikopter, dan sekitar seribu alat berat dari seluruh Indonesia telah dikerahkan. Meskipun demikian, Seskab mengakui bahwa penanganan di lapangan belum sepenuhnya sempurna dan mengajak semua pihak untuk bahu-membahu serta menyebarkan energi positif.
Di tengah upaya penanganan, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Ira Hadiati melaporkan bahwa di Aceh, meski di Bireuen pasokan makanan dan obat-obatan mulai masuk, daerah seperti Bener Meriah dan Aceh Tamiang masih terisolir karena akses terputus, menyebabkan distribusi sulit dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Banyak warga harus menempuh perjalanan kaki berhari-hari untuk mendapatkan kebutuhan. Memasuki pekan ketiga pascabencana, penyakit mulai menjangkiti warga, obat-obatan tidak tersedia, dan lingkungan masih dipenuhi lumpur hingga satu meter, yang menjadi sumber penyakit ISPA. Sanitasi dan air bersih pun sangat mendesak, sementara barak-barak pengungsi belum dibuat, masih berupa tenda-tenda posko darurat.
Meski demikian, Ira menyaksikan semangat juang warga yang luar biasa. Mereka tetap bersyukur atas bantuan sekecil apapun dan menunjukkan solidaritas ‘warga bantu warga’. Keceriaan anak-anak, meskipun mungkin disertai trauma, adalah cara mereka bertahan. Ini menjadi pengingat bahwa kondisi yang terlihat ‘baik-baik saja’ di permukaan tidak berarti kebutuhan mendesak tidak ada.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan akses. Di Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-Batas Sumatra Utara, dan jalan KKA sudah dapat dilalui. Jembatan di Awe Geutah dan Teupin Reudeup, serta jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues dan jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh, termasuk jembatan Bailey, juga sudah bisa diakses. Di Sumatra Utara, wilayah Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal mulai terhubung kembali, meskipun masih ada titik longsor dan jalan amblas. Di Sumatra Barat, jalan nasional Padang-Bukittinggi via Lembah Anai telah mencapai progres perbaikan sekitar 90%, dan jalan provinsi Padang Pariaman-Agam via Malalak sebagian besar sudah dapat diakses.
Perbandingan penanganan bencana ini semakin jelas ketika melihat detail Tsunami Aceh 2004. Ira Hadiati, yang terlibat langsung, merasakan perbedaan signifikan. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 sehari setelah kejadian. Saat itu, semua armada dikerahkan dengan instruksi langsung dari Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun secara intens memantau badan-badan satgas. Pembagian tugas sangat jelas, mulai dari pembersihan lokasi, evakuasi, distribusi logistik, kesehatan, hingga kerja sama internasional yang segera masuk. Semua bergerak satu komando, memungkinkan jalur yang putus segera terhubung kembali melalui jalur darat, udara, dan laut secara taktis dan efisien, bahkan membantu relawan mengelola stres akibat situasi yang sangat sulit.
Mengacu pada dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tanggap Darurat Tsunami Aceh 2004, prioritas utama adalah pemulihan komunikasi, distribusi logistik, relokasi pengungsi, serta pencarian korban. Barak pengungsi dan evakuasi korban selamat dilakukan dalam pekan pertama. Bantuan logistik, tenaga kesehatan, dan obat-obatan langsung tersedia bagi warga terdampak pada minggu pertama. Distribusi bantuan berjalan sejak hari kedua pascabencana seiring perbaikan darurat jalan dan jembatan yang diselesaikan dalam hitungan hari. Pemulihan sanitasi, air bersih, dan listrik memang memakan waktu lebih lama, namun pasokan darurat disediakan sejak bulan pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mencanangkan 12 tata cara penanggulangan bencana dalam tiga hari, meliputi evakuasi intensif, pengelolaan pengungsi, pencarian korban, pembukaan jalur logistik, pemulihan komunikasi, pembersihan kota, pengelolaan bantuan (domestik & internasional), penggunaan dana pemerintah dan sumbangan, pemeliharaan keamanan, penambahan kekuatan TNI/Polri, pelibatan civil society, dan pengendalian operasi yang proporsional. Pada akhir Desember 2004, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ditugaskan berkantor langsung di Aceh, dan bantuan internasional dipersilakan masuk secara besar-besaran.
Pengalaman Videl Jemali di Gempa dan Likuifaksi Palu 2018 juga menawarkan perspektif berbeda. Dengan 4.845 korban meninggal, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah rusak, bencana di Palu, Sigi, dan Donggala juga tidak berstatus bencana nasional. Videl bercerita bahwa rata-rata bantuan baru bisa terdistribusi empat hingga lima hari setelah kejadian, menyebabkan kekacauan dan penjarahan di tiga hari pertama. Bantuan baru terasa merata setelah tiga minggu, ketika banyak bantuan internasional masuk. Tenda pengungsian atau barak juga banyak berasal dari pihak ketiga, termasuk bantuan luar negeri. Pembersihan lokasi memakan waktu sangat lama, dilakukan mandiri oleh warga sebelum Satuan Tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dibentuk empat pekan pascabencana. Pemulihan seperti pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) pun sangat lambat, tertunda hingga bertahun-tahun karena masalah data, kurangnya pelibatan aparat RT/RW, dan sengketa lahan. Pembangunan huntap dari swasta, seperti Buddha Tzu Chi, justru lebih cepat.
Avianto Amri kembali menegaskan bahwa bantuan internasional merupakan keniscayaan. Ia mencontohkan banyak negara lain seperti Filipina (Topan Haiyan 2013), Nepal, Turki, Pakistan, dan negara-negara di Pasifik yang selalu menerima perhatian global dan bantuan saat tertimpa bencana. Indonesia sendiri juga aktif memberikan bantuan ke negara-negara tersebut. Oleh karena itu, menolak bantuan internasional saat Indonesia kesusahan justru dipertanyakan. Ini tidak mencederai harga diri bangsa, melainkan menunjukkan solidaritas dan memperkuat hubungan internasional. Avianto mengingat, saat Gempa dan Likuifaksi Palu, meskipun Presiden Joko Widodo awalnya tidak menetapkan sebagai bencana nasional, inventarisasi menunjukkan kebutuhan akan alat berat, kendaraan logistik, tenaga ahli, dan pendanaan yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya secara nasional. Bantuan internasional akhirnya masuk melalui mekanisme lembaga yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, seperti Palang Merah, dan dampaknya sangat positif.
Meski demikian, pernyataan pemerintah yang menyatakan mampu menangani sendiri dan menolak bantuan asing telah membuat pihak-pihak yang bersedia membantu menahan diri. Avianto sangat menyayangkan hal ini, karena di satu sisi berita menunjukkan besarnya tantangan bencana, namun di sisi lain pemerintah sebagai acuan justru seolah menutup pintu. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan dari luar negeri yang belum ada mekanismenya adalah dalam bentuk government to government. Namun, jika bantuan masuk melalui lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah, hal itu diperbolehkan. Tito mencontohkan kasus pengembalian 30 ton beras oleh Wali Kota Medan Rico Waas yang sempat mengira bantuan dari Uni Emirat Arab itu adalah bantuan pemerintah, padahal berasal dari Red Crescent, sebuah organisasi non-pemerintah.
Kondisi yang terungkap dari berbagai pihak ini menggarisbawahi kompleksitas penanganan bencana di Indonesia. Dari isolasi panjang di Bener Meriah dan Aceh Tamiang yang mengancam kelaparan, seruan “bendera putih” yang menggambarkan situasi genting di Aceh, hingga kisah keluarga yang terjebak di hutan di Sumatra Utara, semua menunjukkan betapa kritisnya respons yang cepat dan terkoordinasi. Peristiwa di Aceh Tamiang yang sempat gelap gulita, diwarnai penjarahan dan bau bangkai seperti “kota zombie”, serta desa-desa di Pidie Jaya yang terkubur lumpur, menambah gambaran suram tentang skala kerusakan. Refleksi dari dua dekade pasca Tsunami Aceh 2004, termasuk cerita para penyintas yang memilih tinggal di zona bahaya dan kisah “bocah ajaib” Martunis Ronaldo, memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan dan pentingnya pemulihan yang komprehensif. Perdebatan status bencana nasional ini pun menjadi cerminan dari tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap individu terdampak dapat dijangkau dan dipulihkan secepat mungkin.