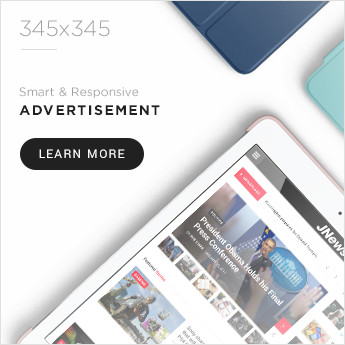Tragedi 1965, Luka yang Tak Kunjung Sembuh: Ketika Tanah Dirampas Atas Nama Ideologi
Enam dekade telah berlalu sejak peristiwa kekerasan 1965 yang menargetkan kelompok komunis dan simpatisannya. Namun, luka akibat tragedi itu masih terasa perih bagi para penyintas. Bukan hanya kehilangan nyawa, peristiwa ini juga merenggut kepemilikan tanah, meninggalkan trauma mendalam yang terus menghantui.
Wahid, seorang penyintas, baru berusia tujuh tahun ketika peristiwa kelam itu terjadi. Ia masih mengingat jelas masa kecilnya di sebuah rumah petak di kawasan Perkebunan Panigoran, Sumatra Utara. Kenangan indah tentang keluarga yang sederhana namun bahagia terus membekas dalam ingatannya.
Meski orang tuanya hanya buruh perkebunan dengan penghasilan pas-pasan, Wahid dan saudara-saudaranya tak pernah kelaparan. Setiap malam, mereka berkumpul di meja makan, berbagi kebahagiaan dan menyantap masakan sederhana namun lezat buatan sang ibu.
Sayur bayam dan tahu tempe goreng adalah menu favorit Wahid. Sesekali, ia meminta ibunya membuatkan telur mata sapi, yang selalu disambut dengan senyum hangat. Bagi Wahid, keluarganya adalah segalanya, sebuah dunia yang membuatnya merasa lengkap dan penuh.
Namun, kebahagiaan itu sirna seketika pada tahun 1965. Ayah Wahid ditangkap tentara tak lama setelah peristiwa itu meletus. Tuduhannya adalah menjadi bagian dari kelompok komunis karena, menurut Wahid, “sering berkumpul bersama buruh-buruh perkebunan yang lain.”
Tanpa proses hukum yang jelas, ayah Wahid dijebloskan ke penjara selama tujuh tahun. Kehidupan Wahid dan keluarganya pun berubah drastis. Ibunya hanya bisa meratapi nasib, tak tahu kepada siapa harus mengadu.
Wahid kecil berusaha memahami apa yang terjadi. Bayangan hari-hari tanpa sosok ayah terus menghantuinya. Meja makan keluarga akan terasa sunyi, pikirnya.
Belum selesai duka merundung, keluarga Wahid harus menghadapi kenyataan pahit lainnya: pengusiran paksa dari rumah yang telah mereka tempati selama sepuluh tahun. “Pihak pemerintahan desa, ditemani tentara, datang ke rumah kami. Mereka meminta dokumen tanah dan kependudukan, katanya mau diperbarui,” tutur Wahid saat ditemui di Padang Halaban, Sumatra Utara.
Karena ketakutan, ibu Wahid terpaksa menyerahkan dokumen-dokumen penting itu kepada perwakilan desa dan militer. Namun, dokumen itu tak pernah kembali. Keluarga Wahid justru mengalami perampasan lahan oleh negara.
Sejumlah tentara bersenjata lengkap mendesak keluarga Wahid untuk segera meninggalkan lahan tempat rumahnya berdiri. Lahan seluas lapangan badminton itu berisi rumah dan kebun kecil yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Sang ibu sempat memprotes, namun dibalas gertakan oleh tentara yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak atas tanah itu karena tidak memiliki dokumen resmi. Tak hanya itu, tentara juga mengancam akan mencap seluruh anggota keluarga Wahid sebagai “komunis” jika mereka tidak mematuhi perintah.
Dengan langkah gontai dan perasaan takut yang mencekam, keluarga Wahid terpaksa mengemasi barang-barang seadanya. Tak lama kemudian, tentara menghancurkan rumah mereka.
“Yang digusur tidak hanya keluarga kami saja, tapi satu desa kena gusur juga,” kenang Wahid. Rumah-rumah warga dirusak, kebun-kebun yang mereka kelola diratakan dengan tanah.
Situasi ini memaksa Wahid dan keluarganya pindah ke Gerojokan Pulo, dekat Panigoran. Di sana, kehidupan mereka sangat berat. Wahid yang masih belia harus bekerja di ladang untuk membantu menghidupi keluarganya.
“Ya macam kami ini enggak sekolah lagi. Itulah beratnya. Kami harus bekerja untuk memberi makan kepada adik-adik kami,” tutur Wahid.
Meski sudah pindah, kenangan tentang rumah di Panigoran tetap melekat kuat dalam ingatan Wahid. Ia masih ingat pohon-pohon hijau yang rindang dan kebun-kebun warga yang penuh dengan tanaman buah-buahan.
Namun, kini, ladang di Panigoran telah berubah menjadi perkebunan sawit. Tragedi 1965 membuka jalan bagi korporasi untuk mengeruk keuntungan dari lahan yang dulunya menjadi milik warga.
Kisah yang dialami Wahid di Sumatra Utara hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang lahir akibat kekerasan 1965. Untuk memahami lebih dalam akar permasalahan ini, kita perlu menelusuri sejarah penguasaan tanah oleh militer yang bermula dari revolusi agraria.
Herlambang Perdana Wiratraman, dosen hukum tata negara dan HAM dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan bahwa penguasaan tanah oleh militer merupakan bentuk dominasi politik negara. Dalam risetnya yang berjudul Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat (2008), Herlambang menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam persoalan tanah seringkali diwarnai dengan kekerasan dan pemaksaan.
Konflik agraria yang melibatkan aksi militer tidak dapat disederhanakan sebagai “tindakan negara” semata. Struktur dan ideologi militer memungkinkan mereka untuk menjadi entitas politik yang otonom. Bahkan, sebelum tragedi 1965, militer sudah memiliki catatan sejarah dalam perampasan tanah warga.
Penelitian Herlambang membagi periodisasi persinggungan militer dan penguasaan tanah menjadi tiga babak.
Periode pertama terjadi pada tahun 1950 hingga 1958, yang dikenal sebagai masa revolusi kemerdekaan dan perang darurat militer. “Kalau pada 1950-an itu karena militer tidak suka dengan diplomasi sipil yang tunduk pada cara-cara berdiplomasi dengan pencuri, maksudnya Belanda, sehingga militer mengambil alih [lahan-lahan penduduk],” ujarnya.
Ketidakcocokan antara militer dan sipil muncul setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) disepakati pada tahun 1949. Militer menilai keputusan KMB terlalu kompromistik. Mereka lebih memilih cara-cara perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan.
Dalam masalah pertanahan, Herlambang mengatakan bahwa “banyak sekali tanah-tanah rakyat yang diserahkan kepada tentara” karena “hubungan rakyat dan tentara cukup baik dan dipengaruhi semangat mempertahankan kemerdekaan.” Rakyat, terutama di wilayah pedesaan, juga memberikan kontribusi berupa makanan dan informasi mengenai posisi tentara Belanda.
Semua itu dilakukan secara sukarela agar cita-cita revolusi 1945 tercapai. Periode kedua terjadi setelah tahun 1958 menuju 1965, dengan konteks nasionalisasi lewat Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.
“Dalam benak masyarakat, dengan nasionalisasi, mereka bisa menduduki tanah-tanah yang dulunya dikuasai Belanda. Karena warga merasa ini negara merdeka,” jelas Herlambang.
“Nah, tiba-tiba undang-undang nasionalisasi justru membuat keadaan berbalik. Bukan warga yang mengklaim tanah itu, tapi perusahaan negara yang mengambilnya, termasuk militer.”
Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (1978) menjelaskan bahwa nasionalisasi memberikan kesempatan bagi tentara untuk mengelola sektor ekonomi. Para perwira Angkatan Darat mengelola perusahaan-perusahaan baru di sektor perkebunan, pertambangan, perbankan, hingga perdagangan.
Memasuki tahun 1960, peran tentara diperluas dengan kewenangan mengawasi korporasi-korporasi asing. Hal ini tidak hanya memperluas fungsi militer, tetapi juga memperkuat kekuatan politik mereka. Kepentingan tentara pada masa ini ditopang oleh sistem politik Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Sukarno.
Tentara merasa puas dengan Demokrasi Terpimpin karena tidak mengusik batas-batas yang telah mereka buat, termasuk dalam persoalan tanah. Bagi Sukarno, keberadaan tentara merupakan modal penting dalam memelihara keamanan dan mewujudkan tujuan politik luar negerinya.
Atas nama nasionalisasi, tentara seolah mendapatkan legitimasi untuk menguasai tanah-tanah yang dinilai berpotensi menjadi aset mereka. Herlambang mencontohkan dengan terbitnya aturan militer yang melarang pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya (1958). Aturan ini kemudian menjadi landasan dalam praktik perampasan lahan.
Konstelasi politik berubah memasuki dekade 1960-an, dengan tiga kekuatan utama berada dalam pusaran kekuasaan: Sukarno, militer, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Kemudian yang ketiga, gelombang yang ketiga ini gelombang yang saya sebut sejak 1965,” ujar Herlambang.
“Peristiwa 1965 itu membuat tanah-tanah rakyat, dalam jumlah yang sangat besar itu, banyak beralih ke militer maupun diserahkan ke perusahaan negara maupun perusahaan swasta,” tandas Herlambang.
Setelah Peristiwa Madiun 1948, militer memandang PKI dengan penuh prasangka. Kekuatan mereka cenderung meningkat pada tahun 1950-an, bahkan masuk ke empat besar Pemilu 1955. Di bawah kepemimpinan D. N. Aidit, PKI fokus pada pengorganisasian massa buruh, terutama petani.
Aidit berpandangan bahwa kelompok tani merupakan massa yang mendominasi di Indonesia dan menjadi subjek utama sumber daya agraria: tanah. Bersama kelas pekerja, Aidit percaya bahwa eksistensi massa petani yang terorganisir adalah elemen krusial bagi partai dalam membangun ideologinya.
PKI kemudian mendekati Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani terbesar waktu itu, agar bersedia berpadu ke dalam satu gerbong yang sama. Keduanya lalu berjalan berdampingan, menyerukan “revolusi agraria.” Revolusi agraria menginginkan para petani kecil dapat menguasai tanah untuk digarap.
Dengan semangat anti-feodalisme dan anti-imperialisme, tanah, baik perkebunan maupun kehutanan, tidak semestinya dimiliki perorangan atau pihak-pihak asing. Negara wajib menyediakan tanah kepada petani dan melindunginya. Tuntutan PKI ini sejalan dengan perhatian Sukarno. Pada tahun 1959, Sukarno berujar bahwa petani harus dibebaskan dari segala bentuk penghisapan.
Gagasan ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. UUPA hendak mengukuhkan dan memperluas akses kepemilikan tanah kepada seluruh rakyat Indonesia di bawah payung landreform atau reforma agraria.
Namun, sejak pertama kali diberlakukan, program landreform tidak benar-benar terpenuhi sesuai tujuannya karena resistensi dari pemilik tanah dan lemahnya pengawasan dari negara. Hal ini mendorong PKI dan BTI mengerahkan massa untuk menempuh “aksi sepihak,” yaitu gerakan merebut lahan yang sudah disewakan atau digadaikan.
Di Kediri, Jawa Timur, PKI dan BTI memobilisasi massa untuk menolak pemindahan lahan perkebunan yang telah digarap para petani. Demonstrasi ini berlangsung masif dan diwarnai kekerasan, menewaskan enam orang dan melukai belasan lainnya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Djengkol.”
Di Sumatra Utara, tepatnya di Bandar Betsy, PKI dan BTI juga melakukan aksi sepihak untuk merebut lahan perkebunan karet. Sedangkan di Sulawesi Selatan, seruan menguasai lahan-lahan milik tuan tanah disambut oleh para petani, yang berujung pada saling serang antara petani dan tuan tanah.
Aksi sepihak menambah pelik penerapan landreform. Di sisi lain, militer semakin terganggu oleh kelompok komunis karena aksi sepihak menyenggol kepentingan-kepentingan lahan yang bertalian dengan tentara. Bagi militer, PKI menjelma sebagai ancaman politik karena basis massa di pedesaan dan perkotaan berkembang pesat.
Kedekatan PKI dengan Sukarno setelah ideologi Nasakom dicetuskan membuat posisi PKI sangat menguntungkan. Kecenderungan militer untuk tidak menyukai PKI sudah terpupuk sejak Peristiwa Madiun 1948. Usai Peristiwa Madiun 1948, militer menganggap PKI pengkhianat.
Saskia Wieringa, profesor sejarah di University of Amsterdam, menambahkan bahwa hubungan tajam antara militer dan PKI juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik saat Perang Dingin bergejolak. Amerika Serikat tidak ingin komunisme menguasai Indonesia. Mereka kemudian membangun sekutu bersama militer guna mencegah komunisme berkembang.
“Dengan memperkuat tentara, Amerika Serikat, diwakili CIA, organ intelijennya, berharap tentara tersebut akan menjadi kekuatan penyeimbang yang sangat kuat terhadap Sukarno, yang didukung oleh PKI,” terang Saskia. “Karena mereka khawatir Sukarno akan membawa Indonesia ke blok komunis. Itu ketakutan besar mereka dan menjadi latar belakang dari banyak peristiwa kemudian,” ujar Saskia.
“Dan itu adalah awal dan dasar, fondasi, kebencian antara kedua kelompok tersebut.” Pada Agustus 1965, Sukarno mengungkapkan pembentukan “Angkatan Kelima” atau tentara rakyat, yang menurut versi PKI terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai.
Tujuan “Angkatan Kelima” adalah untuk menunjang kampanye konfrontasi dengan Malaysia. Militer tidak sepakat dengan inisiatif ini karena dianggap tidak akan efektif dan berpotensi memberikan jalan bagi PKI untuk meraih kekuasaan.
Ketegangan antara PKI dan tentara semakin tajam dan memuncak pada tahun 1965 dengan pembunuhan para perwira Angkatan Darat. Militer memainkan narasi bahwa PKI menjadi dalang atas peristiwa itu sehingga pemberangusan semua yang berkaitan dengan komunisme menjadi sebuah pembenaran.
Namun, Jess Melvin dalam bukunya The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018) menyatakan bahwa sebenarnya militer adalah aktor di balik prahara 1965. Rencana mengudeta pemerintahan Sukarno telah disiapkan jauh-jauh hari dengan konsolidasi struktur komando teritorial dan khusus.
Selain itu, tentara juga melakukan pelatihan kepada warga dalam rangka mengganyang PKI. “Para pimpinan TNI tak ingin terlihat sebagai aktor yang memulai kudeta. Sukarno dan PKI terlalu populer pada masa itu,” jelas Melvin.
“Sebaliknya, seperti dijelaskan John Roosa [penulis Pretext for Mass Murder, 2006] TNI berharap mampu menciptakan sebuah keadaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ‘dalih’ agar militer bisa membungkus tindakan-tindakannya sebagai pertahanan diri.”
Dalih yang dimaksud berupa penculikan dan penghilangan nyawa jenderal-jenderal kunci di TNI, termasuk Ahmad Yani yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Darat. Selanjutnya, Soeharto naik ke pucuk kekuasaan dan menandai dimulainya rezim Orde Baru.
Di bawah Orde Baru, operasi perburuan terhadap orang-orang Kiri dan simpatisannya digalakkan secara masif melalui rantai komando yang diturunkan dari pusat ke daerah. Empat wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, serta Indonesia Timur, menjadi saksi operasi penumpasan. Militer tidak hanya menargetkan nyawa, tetapi juga tanah.
Kebijakan landreform pada tahun 1960-an diterapkan untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah. Petani-petani kecil diharapkan bisa “berdiri di atas kaki sendiri.” Namun, tragedi 1965 mengubah peta yang ada.
Tanah sebagai objek landreform dinilai militer sebagai bagian dari ideologi PKI yang dianggap antagonis. Oleh sebab itu, negara, dalam hal ini diwakili militer, merasa memiliki keleluasaan untuk “menarik kembali” atau merampasnya dari penduduk.
“Kepentingan tentara untuk menguasai tanah-tanah, sebenarnya, sudah muncul sejak era 1950-an, bertepatan kebijakan nasionalisasi,” ujar Dianto.
“Pada 1965, ada satu kesempatan politik yang besar sekali untuk tentara menguasai lebih banyak lagi tanah itu, baik tentara per individu atau kesatuan.” Sasaran tentara adalah tanah-tanah yang berlokasi di lahan landreform atau objek landreform itu sendiri. Bentuknya dapat berwujud tanah milik individu, hasil redistribusi agraria, atau skala besar seperti perkebunan.
Dalam praktiknya, tentara bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa meminta penduduk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dari landreform. Jika tidak bersedia, mereka akan diberi label PKI. Pekerjaan tentara lebih mudah ketika tanah-tanah tersebut sudah berada pada keadaan kosong setelah pemiliknya diringkus karena dituduh sebagai kelompok komunis.
“Yang tanah kosong ini karena pemiliknya sudah dikirim ke Pulau Buru [penjara dan pengasingan] atau sudah menghilang karena, sebagai contoh, terlibat BTI [Barisan Tani Indonesia],” tutur Dianto.
Herlambang menjelaskan bahwa militer yang disokong organisasi teritorialnya di daerah membagi mereka yang bersinggungan secara langsung atau tidak dengan PKI ke dalam tiga klasifikasi:
Pertama, Golongan A, berisikan mereka yang dituding di balik Gerakan 30 September 1965. Kelompok kedua, atau Golongan B, memuat orang-orang yang dituduh aktif mendukung PKI. Sementara yang terakhir, Golongan C, merupakan anggota organisasi massa PKI.
Klasifikasi Golongan C berdampak hebat kepada para petani di pedesaan karena mereka dipandang militer beririsan dengan BTI. Banyak petani, baik anggota BTI maupun bukan, yang ditahan, disiksa, dibunuh, dan diambil paksa tanahnya. Setelah dirampas, tanah-tanah milik petani dan penduduk desa yang sebagian besar hasil landreform ini disertifikasi ulang oleh militer. Pola-pola demikian muncul di banyak daerah, merentang dari Sumatra hingga Jawa.
Penelitian berjudul Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca-1965 di Banyuwangi (2018) memperlihatkan bahwa perampasan lahan di Banyuwangi terjadi dan berpusat di tanah-tanah yang sebelumnya dibagikan untuk landreform. Di Kecamatan Gambiran, misalnya, tanah objek landreform yang dirampas tentara dan pemerintahan desa luasnya mencapai lebih dari 300 hektare. Hal yang sama dapat disaksikan di Kecamatan Pesanggrahan dengan tanah sebesar hampir 400 hektare. Aksi perampasan tanah dibarengi penciptaan teror oleh militer, pejabat desa, sampai pemerintah daerah.
Tidak sedikit pula penguasaan tanah landreform di Banyuwangi juga disertai pemenjaraan dan pembunuhan massal. Di Kecamatan Pesanggaran, sebanyak 111 orang meninggal dalam operasi penghancuran PKI oleh militer pada akhir 1965. Luas lahan yang diambil tentara di kecamatan ini adalah lebih dari 300 hektare.
Pembantaian ratusan orang yang dituduh mendukung PKI didorong pula faktor bahwa pemilih PKI di Pesanggaran merupakan yang terbesar se-Banyuwangi (hampir 20 ribu orang). Bergeser ke Kecamatan Gambiran, sekitar 2.500 warga dituding bagian dari PKI. Jumlah korban tewas tidak ditemukan datanya, tapi diyakini tidak sedikit. Militer menyisir Gambiran untuk mencari serta membalas aksi sepihak yang beberapa waktu sebelumnya ditempuh massa PKI maupun BTI. Luas tanah yang dicaplok militer di Gambiran mencapai 317 hektare. Pemandangan tidak jauh berbeda ditemukan di Kalibaru. Di daerah ini, ribuan orang ditangkap dan dibunuh, selain “sejumlah besar tanah objek landreform yang dirampas.”
Banyuwangi adalah salah satu titik “merah” di Pulau Jawa karena banyak warga yang bersimpati dan mendukung PKI. Pada tahun 1964, posisi PKI di Banyuwangi termasuk mentereng, berjejer di tiga besar partai politik dengan massa yang militan, bersama PNI dan NU. Dari segi implementasi landreform, Banyuwangi menyumbang 1,6% terhadap angka nasional atau 4,8% di Jawa Timur.
Sampai tahun 1964, tanah yang berhasil didistribusikan ulang di Banyuwangi hampir 5.000 hektare dengan petani yang menerimanya berjumlah 13.781 orang. Catatan itu, agaknya, sudah cukup bagi militer untuk menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu daerah utama di Jawa yang harus dibersihkan dari kelompok komunis beserta anasir-anasirnya.
Peristiwa aksi sepihak yang digerakkan massa terafiliasi PKI dan BTI guna menuntut kelancaran landreform semakin memantapkan militer dalam upaya memburu orang-orang Kiri dan kemudian merampas tanah mereka. Militer bergerak dengan mendatangkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Operasi dilangsungkan tidak sebatas menerjunkan pasukan, melainkan menggandeng kelompok sipil yang dilatih serta dipersenjatai—dikenal sebagai paramiliter.
Perampasan tanah secara terstruktur juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian Hilma Safitri, Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Land Reform dan Peristiwa 1965 di Desa Soge, Indramayu (2018), tanah milik 130 warga diambil paksa oleh otoritas.
Pemerintah desa beserta aparat merupakan kelompok yang tidak menyukai kebijakan redistribusi tanah. Pasca-1965, mereka memperoleh momentum untuk menggasak tanah hasil landreform. Puluhan warga setiap harinya dipanggil ke kantor pemerintahan desa. Di sana, aparat militer telah menunggu. Warga diminta memberikan surat kepemilikan tanah. Yang menolak, ditahan selama tiga hari dan dihajar. Di Desa Soge, aparat menyebarkan ketakutan kepada warga dengan menekan narasi “anggota PKI” agar mereka bersedia menyerahkan tanahnya.
Di samping menargetkan mereka yang tergabung dalam PKI, aparat turut menyasar orang-orang yang tidak memiliki garis hubungan dengan kelompok Kiri. Belasan orang tercatat dikriminalisasi membawa embel-embel organ massa PKI seperti Pemuda Rakyat serta BTI. Hasilnya “cukup efektif,” tulis Hilma dalam penelitiannya. Provokasi dan pemaksaan aparat membikin warga tidak mempunyai banyak ruang kecuali memberikan pegangan legal mereka atas tanah ke otoritas.
Penyematan label “komunis” selalu diproduksi ketika militer merampas tanah-tanah rakyat pada 1965. Propaganda militer yang menempatkan PKI sebagai dalang di balik kudeta terhadap pemerintah membuat posisi mereka tak ubahnya “musuh negara.” Pemberian label komunis kerap diikuti dengan penguasaan tanah.
Herlambang menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga cara atau model yang digunakan untuk memanfaatkan tanah-tanah yang disita tersebut.
Pertama, militer menyerahkan tanah yang dirampas kepada negara, dalam hal ini BUMN, untuk dikelola sebagai aset perkebunan negara. “Misalnya, kasus di Ngerangkas Pawon, Badeg, Bapatan, dan Sata, ini empat desa di Kediri, itu [tanahnya] diserahkan ke PT Perkebunan Nusantara XII di Kediri, Jawa Timur,” ucap Herlambang.
Kedua, tanah hasil perampasan dipakai militer untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik untuk kepentingan bisnis maupun fasilitas penunjang kesatuan. Herlambang menjelaskan bahwa di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk Lumajang, Blitar, dan Ponorogo, tanah sitaan sering kali dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Lahan-lahan tersebut diubah menjadi perkebunan tebu yang pengelolaannya diserahkan kepada koperasi-koperasi militer.
“Nah, kalau fasilitas militer itu tergantung [luas lahan]. Kalau kecil, rumah, itu jadi markas koramil. Ada juga [tanah] yang dipakai untuk pusat latihan tempur,” imbuh Herlambang.
Ketiga, tanah-tanah rakyat yang diambil militer dilepaskan kepada perusahaan swasta melalui pemberian fasilitas Hak Guna Usaha (HGU). Modus operandi semacam ini ditemukan di Padang Halaban, Sumatra Utara.
Usai Peristiwa 1965 meletus, militer melakukan operasi penyisiran sekaligus penguasaan tanah-tanah warga yang berada di area perkebunan setempat. Militer menangkapi warga, menuding mereka sebagai anggota BTI, serta mengambil paksa tanahnya. Bagi warga yang tidak terlibat aktivitas politik, militer memanipulasi mereka dengan meminta dokumen kepemilikan tanah, berdalih bahwa pemerintah desa membutuhkannya untuk pembaharuan. Kenyataannya, dokumen warga tidak pernah kembali.
Tanah warga seketika diklaim, dan bagi yang melawan tentara mempunyai amunisi berwujud pelabelan komunis sehingga menyiutkan nyali mereka yang memberontak karena kekerasan merupakan reaksi yang dapat timbul setelahnya. Tidak lama usai tanah berhasil dicaplok, tentara dan negara menyerahkannya kepada perusahaan kelapa sawit dan karet bernama Plantagen Aktiengeschllschaft (Plantagen AG).
Totalnya menyentuh 5.000 hektare, dengan 3.000 hektare sebelumnya diurus dan ditempati warga. Penyerahan tanah ini bisa dibaca sebagai upaya rezim militer Soeharto mewujudkan agenda-agenda pembangunan yang propasar. Salah satu titik balik yang fundamental adalah saat Orde Baru menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1967, hanya berjarak kurang dari lima tahun pasca-1965.
Undang-undang tersebut akhirnya menggeser corak ekonomi Indonesia sekaligus membuka pintu bagi korporasi besar, pemodal, bahkan pemburu rente untuk saling berebut peluang profit yang ditawarkan Soeharto.
Saskia Wieringa bilang pencaplokan lahan atau kapital oleh militer pada 1965 sangat berkelindan dengan bagaimana kekuasaan Soeharto dan Orde Baru disusun. Tanah yang direbut paksa dari rakyat memanfaatkan propaganda komunis merupakan bekal Soeharto dalam memasang tali ikat kepada para pemodal penopang imperiumnya. Setelah militer melapangkan karpet baginya untuk merebut kekuatan dari Sukarno (Orde Lama), rencana Soeharto berikutnya ialah mengatur ekonomi.
Ketika dia sudah memegang perekonomian, “masyarakat mampu dikendalikan,” tambahnya.
“Soeharto sendiri sangat menyadari bahwa jika dia ingin mempertahankan kekuasaan, dia harus membangun sekelompok pengusaha kaya raya di sekitarnya yang nantinya akan membiayai proyek-proyeknya sekaligus memastikan tentara tetap kuat,” tegas Saskia yang terlibat dalam penulisan buku Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2018).
“Jadi, kekuasaan ekonomi dan politik telah, setidaknya sejak saat itu, sangat erat terjalin di Indonesia.” Herlambang menambahkan perampasan lahan oleh militer setelah tragedi 1965 berjalan begitu dahsyat sebab, menurutnya, “militer punya posisi yang sangat kuat di masa rezim otoritarian Orde Baru.” Posisi yang superior itu “membuat terjadinya akselerasi proses perampasan,” tegas Herlambang.
“Tidak mungkin di masa itu melakukan perlawanan terhadap institusi-institusi militer, bahkan terhadap personal-personal militer secara individu.”
“Karena saya temukan juga sejumlah kasus bahwa rumah [warga] itu bisa berganti hanya karena pemilik rumahnya dituduh PKI. Selanjutnya diambil sama militer.”
Warisan 1965: Cap Komunis Terhadap Warga yang Memprotes Kepemilikan Lahan
Seniman, warga pesisir Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, berusia 52 tahun, mempercayai tanah yang dia tinggali sekarang merupakan warisan keluarga yang diturunkan temurun. Prinsip ini diyakini juga oleh mayoritas masyarakat yang hidup di 15 desa lainnya. Walaupun peninggalan keluarga, upaya untuk melindungi lahan secara hukum turut dilangsungkan sejak 1950-an dengan harapan di masa depan tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Namun, warga di Urut Sewu keliru.
“Kalau kami lihat, mereka, pada 1998, mengklaim 500 meter dari bibir pantai. Pada 2007, mereka mengklaim 1.000 meter dari bibir pantai,” jelas Seniman. “Kemudian pada 2009, mereka balik lagi ke 500 meter dari bibir pantai.” “Mereka” yang dimaksud Seniman di sini bukan sembarang pihak: tentara TNI Angkatan Darat (AD).
Hubungan TNI AD dan tanah di Urut Sewu dapat dilacak setidaknya mulai 1970 dan 1980-an tatkala mereka membangun sejumlah fasilitas seperti kantor koramil (komando rayon militer) sampai lokasi uji coba senjata. Waktu itu, warga di Urut Sewu tak keberatan berbagi tempat lantaran TNI meminjam tanah dari masyarakat.
Akan tetapi, pada 1998, TNI AD disebut melakukan pemetaan secara sepihak terhadap tanah seluas 500 meter dari bibir pantai, memanjang 22 kilometer dan melewati 15 desa, untuk lokasi latihan. TNI AD menyatakan area tersebut adalah milik mereka.
Rencana pembangunan infrastruktur penghubung bernama Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) kian menguntungkan militer. Dalam rencana itu, Seniman mengungkapkan, “tidak boleh ada bangunan dan kegiatan apa pun kecuali yang dilakukan TNI.”
“Padahal, di selatan dan utara rencana JJLS itu adalah sumber penghasilan petani di Urut Sewu,” tutur Seniman.
Pemanfaatan lahan di Urut Sewu oleh TNI AD tidak cuma untuk latihan. Pada 2008, Kodam IV/Diponegoro menerbitkan surat persetujuan pengelolaan tanah untuk penambangan pasir besi. Izin diberikan kepada satu perusahaan yang kursi komisarisnya diisi jenderal TNI berbintang.
Warga di Urut Sewu semakin kecewa dan menolak klaim kepemilikan TNI maupun rencana penambangan pasir besi. Masyarakat mendesak TNI AD menunjukkan dokumen yang menyatakan TNI AD berhak atas tanah di Urut Sewu. Izin persetujuan pemanfaatan untuk tambang pasir besi sendiri pada akhirnya dicabut. Tapi, penghapusan izin itu tak serta merta menghalau konflik TNI AD dan warga Urut Sewu.
Aksi tentara yang memagari lahan sepanjang 2013 sampai 2019, sebagai contoh, dikritik masyarakat setempat lantaran menjauhkan upaya pencarian solusi terhadap masalah yang ada. Belum reda betul, per 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AD di sembilan desa.
Pihak Kodam IV/Diponegoro membantah kalau tanah di Urut Sewu milik warga. Mereka menegaskan lahan yang dikelola untuk fasilitas militer adalah peninggalan kolonial yang diserahkan kepada negara sebelum diturunkan ke TNI. Kodam IV/Diponegoro berdalih pertikaian di antara warga dan TNI mengenai lahan di Urut Sewu merupakan hasil dari provokasi dan berita hoaks.
Perjuangan warga Urut Sewu mempertahankan tanahnya tidaklah mudah dan tidak jarang mesti beradu dengan kekerasan. Organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu HAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mencatat dugaan adanya tindakan represif tentara terhadap warga di Urut Sewu pada 2011. Dalam insiden tersebut, sebanyak 14 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Empat tahun berselang, pada 2015, peristiwa serupa terulang dengan empat warga terluka akibat dugaan kekerasan oleh personel TNI AD. Kesamaan dari dua kejadian itu, sebut ELSAM, terduga pelaku tidak pernah diusut.
Selain kekerasan fisik, warga mendapat tekanan berupa intimidasi narasi “komunis.” Menurut Seniman, banyak warga Urut Sewu diancam sebagai “anggota PKI” agar tidak memprotes kepemilikan lahan oleh tentara. “Mereka [tentara] bilang kepada warga bahwa kalau mempertahankan tanah itu seperti [anggota] PKI,” kenang Seniman.
Seniman menambahkan bahwa tentara juga menyebarkan narasi yang menuding PKI sebagai partai yang “tidak nasionalis dan religius.” Propaganda dan “serangan” semacam ini, kata Seniman, tak bisa dimungkiri membuat sebagian warga ketakutan. Akibatnya, mereka yang tadinya gigih menolak klaim kepemilikan lahan oleh tentara akhirnya memilih bungkam.
Pemberian label komunis menjadi taktik umum untuk membungkam masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. Pasca-1965, militer secara konsisten menggunakan pendekatan ini untuk mengamankan kepentingan dan hegemoni mereka, termasuk di isu pertanahan. Bahkan setelah Orde Baru runtuh, taktik “antek komunis” masih digunakan untuk mencap warga yang dianggap “membangkang.”
Apa yang dialami warga Urut Sewu dirasakan pula oleh warga Banyuwangi, kendati tak bersinggungan langsung dengan militer. Delapan tahun yang lalu, rencana eksplorasi dan penambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, mendapat penolakan dari warga setempat. Mereka cemas aktivitas pertambangan berpotensi melahirkan bencana ekologi, salah satunya adalah banjir.
Demonstrasi pun ditempuh, meminta izin pertambangan dicabut demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Tumpang Pitu. Salah satu pemimpin aksi penolakan ini adalah Budi Pego, yang sangat vokal menentang tambang emas. Budi Pego kemudian ditangkap dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme di muka umum setelah aparat menemukan spanduk berlogo palu arit saat dia sedang aksi.
Keberadaan spanduk tersebut, bagi kelompok sipil dan lingkungan, dianggap sebagai salah satu bentuk framing atau pembentukan opini publik. Budi Pego lalu dijerat pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Usaha pengajuan banding sempat dilaksanakan hingga tahap kasasi dan ditolak Mahkamah Agung.
Vonisnya diperberat menjadi empat tahun penjara dari semula 10 bulan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Eksekusi kepada Budi Pego baru dilakukan pada Maret 2023.
“Saya bilang [Tragedi] 1965 itu mengubah lanskap. Maksudnya karena dipelihara oleh rezim stigma PKI-nya itu. Itu yang membuat konflik tanah atau konflik agraria hari ini itu mewarisi situasi perampasan tanah di masa 1965,” terang Herlambang.
Pengalaman pahit serupa dihadapi oleh masyarakat adat Nang
Ringkasan
Artikel ini membahas perampasan tanah yang terjadi secara sistematis pasca Tragedi 1965, di mana warga yang dituduh komunis kehilangan tanah mereka. Kisah Wahid di Sumatra Utara menjadi contoh bagaimana tuduhan komunis digunakan untuk merampas lahan dan menghancurkan kehidupan keluarga.
Penguasaan tanah oleh militer memiliki sejarah panjang di Indonesia, dimulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga nasionalisasi. Setelah 1965, perampasan tanah semakin masif dengan dalih pemberantasan komunisme. Tanah-tanah ini kemudian dikuasai negara, militer, atau diserahkan kepada perusahaan swasta. Warisan tragedi ini masih terasa hingga kini, dengan cap komunis digunakan untuk membungkam warga yang memprotes kepemilikan lahan, seperti yang dialami warga Urut Sewu dan Budi Pego di Banyuwangi.